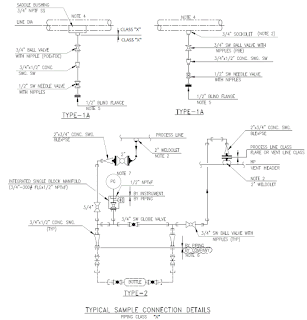|
| Gambar: Piping Layout |
1. Pipe
Ayah Engineer yakin bahwa hampir semua pembaca pernah melihat pipa, baik di rumah, jalan, sekolah, kampus, tempat kerja, dll. Mengutip dari laman wikipedia, bahwa pipa adalah sebuah selongsong bundar yang digunakan untuk mengalirkan fluida -cairan atau gas. Merujuk kepada ASME B36.10M (Welded and Seamless Wrought Steel Pipe), Pipa diidentifikasikan sebagai Nominal Pipe Size (NPS) dalam satuan "inch" yang menunjukkan lebih dekat kepada ukuran Outside Diameter (OD) dimana ukuran dari NPS 1/8 - NPS 12 memiliki size OD yang lebih besar dibandingkan ukuran NPS-nya. Namun untuk ukuran NPS 14 - NPS lebih besar memiliki ukuran OD yang sama dengan NPS-nya. Ada OD berarti ada Inside Diameter (ID) yang merupakan radius bagian dalam yang langsung kontak dengan fluida yang didalamnya. Selisih antara OD dan ID inilah yang dinamakan dengan Wall Thickness atau ketebalan pipa dan . Jika diilustrasikan seperti gambar dibawah:
Thickness pipa yang diatur oleh ASME B36.10M dikelompokkan dengan istilah Schedule (SCH) yang pada awalnya terdiri dari SCH.STD (Standard), SCH.XS (Xtra Strong) dan SCH.XXS (Double Xtra Strong) dan diperluas mulai dari Schedule 10 hingga Schedule 160. Semakin besar nilai Schedule, semakin tebal pipanya dan berpengaruh pada Inside Diameter (ID) yang semakin kecil. Nomor Schedule ini merupakan nilai yang diperoleh dari 1000 P/S, dimana P adalah Pressure dan S adalah Allowable Stress yang keduanya dalam satuan Pounds per Square Inch (PSI).
Kemudian kita akan menemui SCH.10S atau SCH.40S dimana ada penambahan huruf S yang bisa saja sama atau tidak sama dengan dengan Schedule yang tidak ada huruf S. Nah aturan penambahan huruf S ini merujuk pada ASME B36.19M dimana khusus mengatur pada Pipa berbahan material Stainless Steel yang tidak meng-cover seluruh NPS Pipa dari ASME B36.10M.
Ayah Engineer perlu menambahkan juga, selain dari ASME, ada juga pipa yang memakai metric unit system yang diistilahkan dengan DN (Diameter Nominal) dengan satuan milimeter, misalkan DN50 artinya memiliki diameter 50 mm. Ukuran ini dikembangkan oleh International Standards Organization (ISO). Jika dibandingkan dengan NPS, maka inilah konfigurasinya :
Material penyusun pipa yang biasa ditemui di proyek Oil & Gas adalah:
Grup ASME B36.10M
a. ASTM A53 (Carbon Steel)
b. ASTM A106 Gr.B (Carbon Steel)
c. ASTM A333 Gr.6 (Carbon Steel for Low Temperature)
d. ASTM A312 Gr.TP316L (Stainless Steel)
e. API 5L Gr.B (Carbon Steel) → hampir memiliki sifat properties yang sama dengan ASTM A106 Gr.B
2. Fittings
 |
| Gambar: Profil Pipa |
Thickness pipa yang diatur oleh ASME B36.10M dikelompokkan dengan istilah Schedule (SCH) yang pada awalnya terdiri dari SCH.STD (Standard), SCH.XS (Xtra Strong) dan SCH.XXS (Double Xtra Strong) dan diperluas mulai dari Schedule 10 hingga Schedule 160. Semakin besar nilai Schedule, semakin tebal pipanya dan berpengaruh pada Inside Diameter (ID) yang semakin kecil. Nomor Schedule ini merupakan nilai yang diperoleh dari 1000 P/S, dimana P adalah Pressure dan S adalah Allowable Stress yang keduanya dalam satuan Pounds per Square Inch (PSI).
Kemudian kita akan menemui SCH.10S atau SCH.40S dimana ada penambahan huruf S yang bisa saja sama atau tidak sama dengan dengan Schedule yang tidak ada huruf S. Nah aturan penambahan huruf S ini merujuk pada ASME B36.19M dimana khusus mengatur pada Pipa berbahan material Stainless Steel yang tidak meng-cover seluruh NPS Pipa dari ASME B36.10M.
Ayah Engineer perlu menambahkan juga, selain dari ASME, ada juga pipa yang memakai metric unit system yang diistilahkan dengan DN (Diameter Nominal) dengan satuan milimeter, misalkan DN50 artinya memiliki diameter 50 mm. Ukuran ini dikembangkan oleh International Standards Organization (ISO). Jika dibandingkan dengan NPS, maka inilah konfigurasinya :
 |
| Gambar: Tabel NPS - DN (Sumber Piping Handbook) |
Grup ASME B36.10M
a. ASTM A53 (Carbon Steel)
b. ASTM A106 Gr.B (Carbon Steel)
c. ASTM A333 Gr.6 (Carbon Steel for Low Temperature)
d. ASTM A312 Gr.TP316L (Stainless Steel)
e. API 5L Gr.B (Carbon Steel) → hampir memiliki sifat properties yang sama dengan ASTM A106 Gr.B
2. Fittings
Fitting merupakan material penghubung antar pipa atau bisa juga fitting-to-fitting (fitting make-up) yang berfungsi sebagai penyambung dan pemberhentian aliran dan juga mengubah size atau aliran pipa. Fittings dikelompokkan sesuai tipe ujung penyambungnya, misal Butt-Welding (BW), Socket-Welding (SW), Screwed (atau Threaded). Contoh fittings yaitu 90⃘ & 45⃘ Elbows (Short dan Long Radius), Equal & Unequal Tees, Concentric & Eccentric Reducer, Swage Nipple, Cap, Stub-end, Sockolet, Weldolet, Coupling & Unions.
a. Butt-Welded (BW) Fittings
BW Fittings memiliki sudut 30⃘ pada bentuk ujungnya sebagai penyiapan area welding yang terdiri dari root gap area dan landing area. Standar BW Fittings diatur dalam ASME B16.9 yang mengatur dari jenis material, dimensi, toleransi, rating dan testing. Material yang dicover oleh standar tersebut adalah ASTM A234 (Carbon Steel), ASTM A403 (Stainless Steel) dan ASTM A420 (CS Low Temp.). Berikut ini gambar penyiapan area welding serta contoh BW Fittings.
b. Socket-Welded (SW) Fittings
Tipe SW lebih mudah untuk difabrikasi dan di fit-up. Si pengelas atau welder pun tidak harus memiliki skill yang tinggi seperti yang diperlukan pada tipe BW joint. Tipe SW lebih disukai dibanding tipe Screwed atau Threaded karena dapat menghindarkan potensi kebocoran yang kadangkala terjadi pada tipe Screwed. Rating yang biasa ditemui pada SW Fittings ialah rating 3000# dan 6000#. Standar SW Fittings diatur dalam ASME B16.11 dan umumnya banyak ditemui material forging seperti pada ASTM A105 (Carbon Steel) dan A182 F316 (Stainless Steel).
c. Screwed or Threaded Fittings
Fitting ini memiliki ulir pada sistem penyambungannya sehingga cukup cepat dikerjakan. Namun karena ada potensi kebocoran pada sambungannya, terkadang diakali dengan seal weld agar tidak bocor. Tipe ini dikelompokkan berdasarkan ratingnya, yaitu 3000# dan 6000#. Berikut adalah gambar dari Screwed Fittings. Sama halnya dengan SW Fittings, Standar Screwed Fittings diatur dalam ASME B16.11 dan material forging yang banyak ditemui di pasaran.
3. Flanges
Flanges merupakan penghubung utama dari pipa ke Valve atau ke fitting yang memiliki variasi ukuran dan rating yang dihubungkan dengan bolting. Standard yang biasa digunakan pada Flanges yaitu ASME B16.5, mulai dari jenis, rating, ukuran dan tipe facing. Rating yang dikelompokkan meliputi rating 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# dan 2500#. Pada ukuran, mulai dari 1/2", 3/4", 1", 2", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22" dan 24". Namun masih ada beberapa standar lain yang digunakan, namun khusus yang akan dibahas lebih kepada ASME B16.5. Material digunakan adalah material forging, seperti ASTM A105 (Carbon Steel) dan ASTM A182 F316 (Stainless Steel) dan beberapa material lainnya.
Jenis Flange terdiri atas WN Flange, Socket Flange, Slip-On Flange, Lap Joint Flange, Hub Flange, Orifice Flange dan Blind Flange. Berikut ini detail penjelasannya.
a. WN Flange
WN (Welding Neck) Flange adalah jenis flange yang paling umum digunakan di industri skala besar, bentuknya perpaduan antara hub yang di-taper dengan transisi panjang pipa dengan thickness tertentu. Hub ini yang akan memiliki peranan penting dalam penguatan flange yang menahan kekuatan dan tahanan aliran yang ada di dalamnya. Tipe joint flange ini ialah Butt-Welded.
b. SW Flange
SW (Socket Welding) Flange biasanya digunakan untuk ukuran dibawah 2 inch. Sesuai dengan namanya, tipe joint flange ini ialah Socket-welded. Berikut adalah gambar dari Socket-Welded Flange.
Untuk menghindari pocket atau aliran yang masuk pada celah diantara sambungan flange dan pipa, bagian internal flange yang langsung kontak dengan pipa di-grinda seperti pada skema dibawah ini.
c. Slip-on Flange
Sebenarnya untuk flange tipe ini, Ayah Engineer jarang menggunakannya. Namun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa tipe ini lebih murah dibanding WN Flange dan lebih mudah diinstal karena tidak membutuhkan akurasi yang tinggi pada saat assembly. Akan tetapi, final cost untuk instalasi tidak jauh berbeda dengan WN Flange dan kekuatannya 2/3 dan durasi fatigue 1/3-nya dari WN Flange. Berikut gambar & skema join dari Slip-on Flange.
d. Lap joint Flange
Lap joint flange terdiri atas flange itu sendiri dan stub-end yang mengijinkan 2 material berbeda. Sebagai contoh, Ayah Engineer menemukannya pada line Cu-Ni dimana stub-end memiliki material yang sama dengan pipa, yaitu Cu-Ni sedangkan flange terbuat dari material Carbon Steel Galvanise. Tentu hal ini mengurangi cost dari material itu sendiri, sedangkan saat instalasi lebih mudah dilakukan saat alignment bolting hole. Berikut adalah contoh gambar Lap Joint Flange.
e. Blind Flange
Blind Flange di desain untuk menutup atau memblokadekan aliran dari piping, nozzle atau valve. Karena fungsinya tersebut, maka tipe ini yang paling besar menerima stress. Namun thickness dari Flange ini sudah diatur di dalam ASME untuk menerima pressure dan temperature tertentu. Berikut adalah contoh Blind Flange tipe RF & Ring Joint.
f. Orifice Flange
Orifice flange digunakan untuk mengukur flow rate yang ada di dalam pipeline sehingga mengurangi hot tap pada pipa. Orifice flange memiliki variasi ukuran dan jenisnya yang meliputi weld neck, slip-on dan screwed.
Flange Facing
Flange kemudian dikelompokkan juga berdasarkan tipe facing atau permukaannya yaitu Raised face, Flat face dan Ring Joint.
- Raised face (RF)
RF adalah tipe yang paling umum kita temukan di pasaran. ketinggian face ini dibedakan berdasarkan rating, yaitu 1.6mm untuk rating 150# dan 300#. Sedangkan 6mm untuk rating di atasnya. Jika diperhatikan lebih seksama, permukaan jenis RF dipolakan dalam bentuk concentric maupun spiral groove sedalam kira-kira 0.4mm.
- Flat face (FF)
FF adalah tipe facing yang rata alias tidak memiliki tambahan ketebalan permukaan. Perbedaan gasket yang digunakan pada RF dan FF ialah pada RF lingkaran gasket hanya sebesar diameter raised face-nya saja, namun pada FF lingkaran gasket yang digunakan sebesar outside diameter flange. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bahaya crack pada flange FF ketika dikencangkan.
- Ring Joint (RJ)
Ring Joint adalah tipe flange yang digunakan untuk rating yang tinggi sehingga harganya cukup mahal. Sesuai namanya, facing flange ini mempunyai space untuk disisipkan ring gasket yang bisa berbentuk oval atau octagonal.
Referensi:
1. www.wikipedia.org
2. Piping Handbook
3. Gambar sebagian dari google
a. Butt-Welded (BW) Fittings
BW Fittings memiliki sudut 30⃘ pada bentuk ujungnya sebagai penyiapan area welding yang terdiri dari root gap area dan landing area. Standar BW Fittings diatur dalam ASME B16.9 yang mengatur dari jenis material, dimensi, toleransi, rating dan testing. Material yang dicover oleh standar tersebut adalah ASTM A234 (Carbon Steel), ASTM A403 (Stainless Steel) dan ASTM A420 (CS Low Temp.). Berikut ini gambar penyiapan area welding serta contoh BW Fittings.
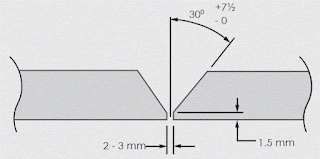 |
| Gambar: Skema Butt Weld |
 |
| Gambar: BW Fittings |
b. Socket-Welded (SW) Fittings
Tipe SW lebih mudah untuk difabrikasi dan di fit-up. Si pengelas atau welder pun tidak harus memiliki skill yang tinggi seperti yang diperlukan pada tipe BW joint. Tipe SW lebih disukai dibanding tipe Screwed atau Threaded karena dapat menghindarkan potensi kebocoran yang kadangkala terjadi pada tipe Screwed. Rating yang biasa ditemui pada SW Fittings ialah rating 3000# dan 6000#. Standar SW Fittings diatur dalam ASME B16.11 dan umumnya banyak ditemui material forging seperti pada ASTM A105 (Carbon Steel) dan A182 F316 (Stainless Steel).
 |
| Gambar: Contoh SW Fitting |
 |
| Gambar: Skema Socket-Welded |
Fitting ini memiliki ulir pada sistem penyambungannya sehingga cukup cepat dikerjakan. Namun karena ada potensi kebocoran pada sambungannya, terkadang diakali dengan seal weld agar tidak bocor. Tipe ini dikelompokkan berdasarkan ratingnya, yaitu 3000# dan 6000#. Berikut adalah gambar dari Screwed Fittings. Sama halnya dengan SW Fittings, Standar Screwed Fittings diatur dalam ASME B16.11 dan material forging yang banyak ditemui di pasaran.
 |
| Gambar: Contoh Screwed Fittings |
3. Flanges
Flanges merupakan penghubung utama dari pipa ke Valve atau ke fitting yang memiliki variasi ukuran dan rating yang dihubungkan dengan bolting. Standard yang biasa digunakan pada Flanges yaitu ASME B16.5, mulai dari jenis, rating, ukuran dan tipe facing. Rating yang dikelompokkan meliputi rating 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# dan 2500#. Pada ukuran, mulai dari 1/2", 3/4", 1", 2", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22" dan 24". Namun masih ada beberapa standar lain yang digunakan, namun khusus yang akan dibahas lebih kepada ASME B16.5. Material digunakan adalah material forging, seperti ASTM A105 (Carbon Steel) dan ASTM A182 F316 (Stainless Steel) dan beberapa material lainnya.
Jenis Flange terdiri atas WN Flange, Socket Flange, Slip-On Flange, Lap Joint Flange, Hub Flange, Orifice Flange dan Blind Flange. Berikut ini detail penjelasannya.
a. WN Flange
WN (Welding Neck) Flange adalah jenis flange yang paling umum digunakan di industri skala besar, bentuknya perpaduan antara hub yang di-taper dengan transisi panjang pipa dengan thickness tertentu. Hub ini yang akan memiliki peranan penting dalam penguatan flange yang menahan kekuatan dan tahanan aliran yang ada di dalamnya. Tipe joint flange ini ialah Butt-Welded.
b. SW Flange
SW (Socket Welding) Flange biasanya digunakan untuk ukuran dibawah 2 inch. Sesuai dengan namanya, tipe joint flange ini ialah Socket-welded. Berikut adalah gambar dari Socket-Welded Flange.
 |
| Gambar: SW Flange |
Untuk menghindari pocket atau aliran yang masuk pada celah diantara sambungan flange dan pipa, bagian internal flange yang langsung kontak dengan pipa di-grinda seperti pada skema dibawah ini.
 |
| Gambar: Skema Joint SW Flange |
c. Slip-on Flange
Sebenarnya untuk flange tipe ini, Ayah Engineer jarang menggunakannya. Namun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa tipe ini lebih murah dibanding WN Flange dan lebih mudah diinstal karena tidak membutuhkan akurasi yang tinggi pada saat assembly. Akan tetapi, final cost untuk instalasi tidak jauh berbeda dengan WN Flange dan kekuatannya 2/3 dan durasi fatigue 1/3-nya dari WN Flange. Berikut gambar & skema join dari Slip-on Flange.
 |
| Gambar: Slip-on Flange & Skema penyambungan |
Lap joint flange terdiri atas flange itu sendiri dan stub-end yang mengijinkan 2 material berbeda. Sebagai contoh, Ayah Engineer menemukannya pada line Cu-Ni dimana stub-end memiliki material yang sama dengan pipa, yaitu Cu-Ni sedangkan flange terbuat dari material Carbon Steel Galvanise. Tentu hal ini mengurangi cost dari material itu sendiri, sedangkan saat instalasi lebih mudah dilakukan saat alignment bolting hole. Berikut adalah contoh gambar Lap Joint Flange.
 |
| Gambar: Lap Joint Flange |
e. Blind Flange
Blind Flange di desain untuk menutup atau memblokadekan aliran dari piping, nozzle atau valve. Karena fungsinya tersebut, maka tipe ini yang paling besar menerima stress. Namun thickness dari Flange ini sudah diatur di dalam ASME untuk menerima pressure dan temperature tertentu. Berikut adalah contoh Blind Flange tipe RF & Ring Joint.
 |
| Gambar: Tipe Blind Flange |
f. Orifice Flange
Orifice flange digunakan untuk mengukur flow rate yang ada di dalam pipeline sehingga mengurangi hot tap pada pipa. Orifice flange memiliki variasi ukuran dan jenisnya yang meliputi weld neck, slip-on dan screwed.
 |
| Gambar: Orifice Flange |
Flange Facing
Flange kemudian dikelompokkan juga berdasarkan tipe facing atau permukaannya yaitu Raised face, Flat face dan Ring Joint.
- Raised face (RF)
RF adalah tipe yang paling umum kita temukan di pasaran. ketinggian face ini dibedakan berdasarkan rating, yaitu 1.6mm untuk rating 150# dan 300#. Sedangkan 6mm untuk rating di atasnya. Jika diperhatikan lebih seksama, permukaan jenis RF dipolakan dalam bentuk concentric maupun spiral groove sedalam kira-kira 0.4mm.
 |
| Gambar: Raised face |
- Flat face (FF)
FF adalah tipe facing yang rata alias tidak memiliki tambahan ketebalan permukaan. Perbedaan gasket yang digunakan pada RF dan FF ialah pada RF lingkaran gasket hanya sebesar diameter raised face-nya saja, namun pada FF lingkaran gasket yang digunakan sebesar outside diameter flange. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bahaya crack pada flange FF ketika dikencangkan.
 |
| Gambar: Flat face |
Ring Joint adalah tipe flange yang digunakan untuk rating yang tinggi sehingga harganya cukup mahal. Sesuai namanya, facing flange ini mempunyai space untuk disisipkan ring gasket yang bisa berbentuk oval atau octagonal.
 |
| Gambar: Ring Joint |
Referensi:
1. www.wikipedia.org
2. Piping Handbook
3. Gambar sebagian dari google